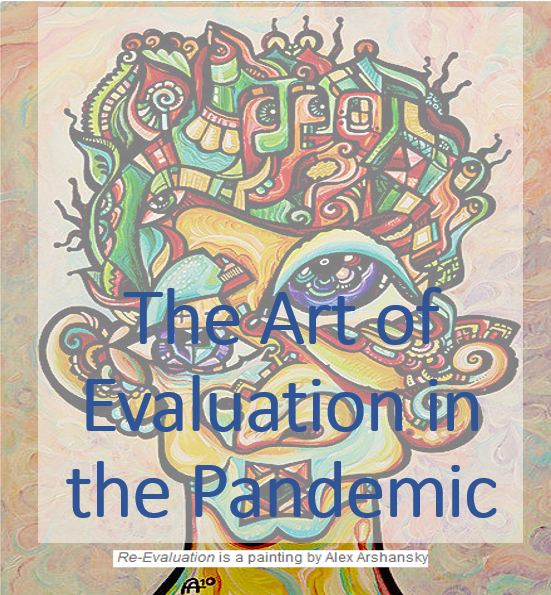Oleh: Dominggus Elcid Li
Hobi mengisi TTS alias Teka-Teki Silang itu banyak manfaatnya, terlebih di era Covid-19. Jika anda adalah penggemar kolom Teka-Teki Silang atau Sudoku di koran atau buku kecil setengah lembar HVS untuk mengasah otak agar tak cepat lupa, atau sekedar ingin membunuh sepi diantara waktu yang enggan diberi makna agar tak terlalu melankolis, maka mungkin anda adalah calon pemimpin yang lama tersembunyi. Ya, mungkin juga kota itu city-state, bisa juga satu negara dengan banyak kota—dengan sekian desanya. Tapi, itu ya hanya jika anda memang mau, sebab tidak banyak lagi penggemar Teka-Teki Silang atau Sudoku yang mau menjadi ‘pejabat publik’. (Bagi yang belum pernah main Sudoku, kalau Teka-Teki Silang itu adalah deretan menurun mendatar kata-kata, Sudoku itu deretan angka-angka.)
Lalu apa urusannya Teka-Teki Silang dan atau Sudoku dengan Covid-19? Ya, untuk menyelesaikan Teka-Teki Covid-19, hal utama yang perlu diperhatikan adalah anda tidak berpikir untuk satu kata saja. Misalnya kata itu ‘ekonomi’ atau ‘kesehatan’. Katakan bahwa kata ‘ekonomi’ adalah jawaban mendatar, dan kesehatan adalah jawaban menurun dengan titik pertemuan pada huruf ‘k’. Lalu kemudian disambung dengan kata ‘pertanian’ atau ‘perdagangan’, atau bahkan ‘pariwisata’ di pojok bawah sebelah kanan mendatar. Permainan ini membantu orang menulis benar dengan berpikir tentang banyak hal, misalnya mencegah agar PAD (Pendapat Asli Daerah) tidak hilang total, tidak mungkin dilakukan tanpa langkah pencegahan maupun penanganan Covid-19 yang tuntas dan segera. Bermain TTS mengajak kita belajar mengoreksi atas nama keterkaitan.
Mungkin anda langsung menjawab, ‘Wah, ternyata mudah menjadi pemimpin publik!’ Besok saya mau jadi presiden, atau walikota, atau mungkin mau jadi Bu Kades dulu sebagai ajang latihan. Tapi ya sabar dulu, bukan itu saja. Bayangkan jika Teka-Teki Silang itu kita ganti jadi Sudoku. Anda yang pernah menjadi juara matematika tingkat kecamatan mungkin langsung berteriak ‘Ah, gampang!’ Persoalannya agak sedikit lebih rumit karena dalam Teka-Teki Covid-19, baik Teka-Teki maupun Sudoku ada dalam satu kolom yang sama, dan beberapa kata belum ditemukan, dan beberapa angka itu sifatnya tak terhingga alias infinite…
Tapi kita jangan masuk ke sana dulu, agar tidak disebut penggemar Novel Utopia. Cukup di bagian dua kata pertama di atas. Ekonomi mendatar. Kesehatan Menurun. Dengan titik pertemuan pada huruf ‘K’. Agar ekonomi bisa bergerak, kesehatan juga harus disentuh. Dan agar kesehatan bisa bergerak, ada kata ‘Teknologi’ yang bertemu dengan huruf ‘T’ pada Kesehatan.
Sayangnya para pejabat publik kita bukan lah penggemar Teka-Teki Silang apalagi Sudoku. Mereka lebih terbiasa hanya menggunakan ‘satu kata’. Kata itu entah ‘ekonomi’, ‘untung’, ‘rugi’, ‘pailit’, ‘bangkrut’. Karena tidak biasa main Teka-Teki, mereka tidak terbiasa menjawab serentak, bahwa antara ekonomi dan kesehatan itu bukan lah pilihan tunggal, tetapi dijawab dalam satu hela nafas. Salah menjawab, hanya membawa kematian.
Kecenderungan terbiasa menjawab ‘kata tunggal’ sebagai jawaban, memang tidak pas untuk main Teka-Teki Silang Covid-19. Sebab ketika yang dipikir hanya satu kata awal, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kata-kata berikut, kolom-kolom Teka-Teki Silang Covid-19 itu tentu kosong, atau tidak terisi.
Berhadapan dengan Teka-Teki Silang Kehidupan yang sulit ada kecenderungan orang segera meninggalkan permainan, atau bahkan melemparkan buku Teka-Teki ke dalam tong sampah sambil berseru, “Ini permainan buang-buang waktu, dan orang sudah mati.”
Ya, persoalannya kematian bagi setiap manusia itu pasti. Tetapi kematian banyak orang dalam rentang waktu yang agak sama katakan lah bagi ‘sebuah bangsa’ amat terkait dengan keputusan dan kerelaan para pemimpinnya untuk main Teka-Teki Silang dengan baik. Tidak hanya berpikir soal satu kata. Tidak hanya berpikir untuk diri sendiri.
Sehingga untuk bisa bermain, harus agak dewasa. Tidak boleh cemberut, lalu berkata “Saya ingin jadi virus untuk lawan Corona!” Ya, mungkin bisa, dalam bentuk ‘vaksin’, jika anda seorang peneliti biomolekuler yang nongkrong di Eijkman, atau kantor sejenis ini. Bisa juga anda mungkin menjawab ‘Saya ingin mencoba mendekati kematian, berikan saya virus corona, saya ingin kenalan dengannya.’ Tapi itu kan masih soal ‘Saya’. Bukan soal virus. Dalam Teka-Teki Covid-19, konsep bahwa saya penting, itu agak tidak penting. Sebab tanpa mengenali secara spesifik spike protein S1, protein permukaan pada virus SarCov2—bagian yang pertama berikatan dengan sel inang sebelum infeksi terjadi, tidak mungkin ada vaksin. Di sisi ini upaya untuk mencoba mengerti asal muasal virus corona bisa berkembang tidak terkendali tanpa mampu dikontrol oleh elemen lain, menjadi renungan tersendiri. Seharusnya riset inti semacam ini dibiayai negara, tetapi ketika negara dikuasai gerombolan perompak-pedagang, isinya kita cuma jadi distributor alat kesehatan bin toekang catoet, meskipun kaum ini sering disebut sebagai yang moelia pedjabat.
Di level industrialis, sudah lama sekian juta ‘saya’ ini merasa menguasai Planet Bumi ini, dan menganggap yang lain ada dalam kendali tangan Si Saya. Upaya melihat kembali rumah bersama dimulai di Eropa lewat renungan Laudato Si yang menjadi bagian percakapan di ruang dalam. Bahkan Si Charles, mantan suami Putri Diana, juga mengulang hal yang sama dalam World Economic Forum di awal bulan ini, ini saatnya memikirkan ulang ekonomi yang berkelanjutan. Tambang mangan dan semen, jelas bukan ya!
Karena Teka-Teki Covid-19 ini luas halamannya tidak sebesar kolom Teka-Teki Silang di Surat Kabar Minggu, tetapi ukurannya sebesar gabungan halaman muka-belakang Surat Kabar Harian, untuk mengisinya butuh kerjasama dengan banyak orang.
Masalahnya ada dua. Pertama, sudah lama kita terbiasa menjawab satu kata, bukan Teka-Teki Silang (mendatar-menurun). Kedua, sudah lama kita berpikir sendiri-sendiri dan bekerja sendirian pula sehingga untuk mengisi Teka-Teki sebesar dua kali halaman koran tidak mudah. Bagaimana mendengar jawaban 30 kawan lain? Atau 5 kawan terdekat yang ada dalam formasi elemen radikal bebas, dan bukan sekedar satuan setengah lusin kurang yang identik? Bahkan di titik ekstrim setengah lusin kurang identic ini ada dalam tawanan imajinasi jenis kelompok yang tersesat secara kolektif, hanya membawa kehancuran pada hidup bersama.
Sebenarnya itu bukan lah hal sulit, jika mau belajar bermain Teka-Teki, dan mau belajar bermain bersama-sama mengisi kolom-kolom Teka-Teki Silang.
Lho kok bermain? Ya, untuk melupakan sejenak ‘ancaman kematian karena salah mengisi kolom’, hal yang paling mudah dibayangkan adalah menganggap ini sekedar sebuah permainan. Kita hanya lah anak-anak yang sedang belajar. Agar beban itu sedikit ringan, dan kita bisa hela nafas seirama lagu zaman kita masih anak-anak, dan menjadi pusat perhatian seisi rumah.
Setiap orang pasti pernah menjadi anak-anak. Tetapi tidak setiap orang pernah mengalami rumah yang penuh tawa. Tidak semua orang beruntung. Makanya ‘Negara’ hadir untuk membantu keluarga, maupun anak-anak yang tidak diberi kesempatan itu.
Lalu ketika negara hanya menempatkan manusia sekedar kawanan (herd), yang dekat sekali dengan konsep ke-hewan-an, dan bukan ke-manusia-an, apakah itu masih disebut Negara? Supir angkot sebuah kota, atau sebuah negara mungkin menjawab ‘Kita tidak punya pilihan’.
Persoalannya, tidak semua pilihan itu terbuka, jika sejak awal ‘logika teka-teki silang’ tidak dipakai. Karena antara satu kata, atau angka sangat terkait dengan kedudukan kata dan angka yang lain pula. Untuk melihatnya butuh seribu mata pemain Teka-Teki.
Nah, rumitnya jika yang diajak untuk bermain bukan pemain Teka-Teki Silang, tetapi mereka yang diajak untuk menemani ‘bermain’ adalah pedagang setengah tukang catut. Baru tiba di kolom pertanyaan kedua, mereka sudah beramai-ramai mengajak, ‘Bagaimana kalau kita jual saja kolom Teka-Teki Silang ini, dapat berapa duit?’
Ini jelas jadi soal. Sebab meskipun anda tahu jawaban Teka-Teki, tetapi dalam mengatur kehidupan umum, ada Pemilu (Pemilihan Umum). Tapi kan, sejak lama Pemilu itu dijual bukan? Bahkan biasanya biar menambah unsur ‘kesegeraan’ yang membuat Pemilu itu serasa penting banget, biasanya ditambah unsur ‘hidup-mati’. Ya, agama. Sehingga makin hari yang terpilih orangnya makin lucu-lucu. Bahkan jika terlalu lucu, bikin kepala pening, sehingga perlu diganti sesering mungkin seperti pampers.
Lalu bagaimana?
Agar bisa bermain dengan baik kita perlu menerima logika Teka-Teki Silang maupun Sudoku. Berikutnya, karena butuh seribu mata anak-anak bahagia yang dipakai untuk menjawab maka perlu ada sistem (bersama). Sayangnya, sistem ini tidak mungkin dibangun, jika hanya dimulai dan diakhiri dengan kata ‘saya’. Karena kita sudah tahu, itu pasti salah. Apalagi jika dimulai dari kelompok yang suka mencuri, dan memanipulasi.
Saya dalam pengertian pejabat publik hanya berarti jika mampu menerjemahkan kehendak umum (general will) itu kata Si Rosseau. Saya mungkin mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan kolektif jika ada dukungan maupun publik berkenan menjatuhkan hukuman untuk yang melanggar, dan diberikan hukuman kata Si Weber dengan konsepnya soal ‘legitimasi’ satu abad kemudian setelah Rosseau.
Lalu, apa hukumannya untuk yang masih menganggap ‘Negara adalah Saya’? Konsep ini diperkenalkan oleh Raja Louis XIV tahun 1655 sebagai _L’etat, c’est moi_. Konsep ini lah yang dilawan Rosseau, yang menjadi salah satu kontributor ide dalam Revolusi Perancis (1789-1799). Pertanyaan di atas, dengan dijawab dengan kesadaran warga, yang menggantikan bangunan monarki absolut lewat revolusi. Embrio Republik pun hadir dengan munculnya Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara (Declaration des droits de l’homme et du citoyen). Itu kalau orang niat bernegara seperti orang-orang di negerinya Macron, yang terampil sekali menggunakan media, dan menjadi pemikir di garda republik. Sedang di sini, berpolitik masih seperti orang piknik, tidak ada pikirannya.
Jika hari-hari ini, di tahun 2020 formasi Negara yang berbentuk republik yang dihantam krisis virus, berbalik arah untuk menegakan prinsip kehewanan, maka telah cukup jauh virus berhasil menggoyahkan pikiran moderen tentang (warga) negara. Bahkan sebagian masuk kembali ke dalam konsep ruang sakral pencipta, dalam wawasan manusia yang terbatas, atau malah sekedar atas nama hubungan darah (primordial). Tetapi, sebagian besar yang muncul di era krisis ini adalah kombinasi antara kedua hal ini, ditambah dengan nalar pedagang setengah tukang catut, yang tidak ada nalarnya. Sebab nasib sekian juta warga disederhanakan seperi mereka sedang bermain lempar koin, ‘untung’ atau ‘rugi’.
Sedangkan posisi sekarang membutuhkan kebersamaan untuk menyelesaikan Teka-Teki sebesar dua kali halaman koran. Di era Revolusi Perancis, makhluk bernama virus belum lagi dikenal. Dalam dunia virologi, virus pertama, Tobacco Mosaic Virus disumbangkan oleh Ivanovsky di tahun 1892 dan Beijerinck tahun 1898. Sedangkan kata virus sendiri mulai dipakai sejak tahun 1728, untuk menyebutkan agen yang menyebabkan penyakit menular. Sedangkan sebagai sebuah konsep modern baru muncul di era Ivanovsky-Beijerink.
Kata sebagai konsep, dan angka sebagai indikator waktu sedikit membantu kita untuk berjalan, dan melihat tanda rambu bahaya, seperti panduan pertanyaan mendatar dan menurun dalam Teka-Teki Silang agar tidak keliru menjawab. Sebagai warga negara sebuah republik kita mempunyai hak untuk menolak keputusan yang keliru, maupun di saat yang bersamaan bekerjasama untuk menjaga warga negara yang lain tidak dibiarkan mati. Sebab membiarkan kematian warga negara adalah anti tesis dari konsep republik maupun warga negara. Persaudaraan (Fraternite) dan Persamaan (Egalite) adalah salah dua dari tiga konsep kunci republik. Dalam kedua konsep ini dimengerti bahwa ‘mereka yang mati adalah saya’, atau dalam Bahasa Dawan, bahasa daerah terbesar yang dipakai di Timor Barat, ungkapannya menjadi ‘Hit auk bian’, atau anda adalah bagian dari tubuh kita. Ini lah konsep dasar tubuh politik republik.
Sebelum lupa, di era krisis akibat pandemi, sebelum mengisi jawaban atas pertanyaan TTS No.2, pertanyaan No.1 perlu dilengkapi yang isinya soal kesehatan harus di-isi dengan benar, agar kita tidak hanya menunda kekalahan, atau masuk dalam krisis panjang tanpa ujung. Di sisi ini bakti terhadap publik menjadi syarat bergerak. Tanpa kecintaan pada manusia yang paling lemah, politik hanya kegiatan yang tidak ada artinya. Sekedar sirkus kawanan hewan, dan kumpulan para predator buas.
Di titik ini ketika konsep warga negara kosong dan diabaikan, partai-partai politik terasa semakin hari semakin menjadi ancaman untuk kehidupan rakyat. Trend berburu rente sampai mati jadi kebiasaan kolektif. Berhadapan dengan fenomena ini rakyat perlu belajar bergerak bersama, mengisi teka-teki silang sendiri, tetap gembira, dan memastikan agar Covid-19 tidak menggerus daya kritis.
*Sosiolog, peneliti di IRGSC, Anggota Forum Academia NTT